Selalu ada yang pertama buat semua hal. Pertengahan bulan Mei lalu, saya ditantang penerbit buat menulis buku dongeng. Wah, seneng banget karena memang sudah lama pingin bisa menulis kisah-kisah menarik buat anak-anak. Pingin membukukan dongeng-dongeng yang sering saya ceritakan ke anak-anak saya, tepatnya.
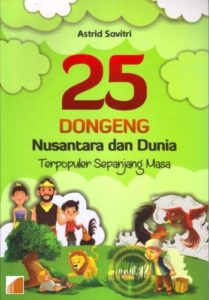
Sayangnya, saya salah menangkap maksud penerbit. Mereka maunya saya re-write kumpulan dongeng nusantara, bukan menulis dongeng baru. Re-write di sini artinya mem-parafrase dongeng-dongeng populer dengan bahasa versi saya, tapi kisahnya tetap ikut pakem. Kecewa? Ya, sedikit. Tapi karena sudah kadung senang, ya tetap saja saya jalan. Pikir saya, “Ah, lebih mudah, nih! Kan tinggal kumpulkan materinya, sumbernya banyak, lantas ditulis ulang dengan kalimat sendiri.”
Kalau dilihat dari proses itu, ya sih lebih mudah. Makanya proses penulisan buku dongeng bisa saya selesaikan dalam dua minggu. Tapi ternyata justru di sini tantangannya.
Saya termasuk orang yang telanjur skpetis dengan dongeng-dongeng yang sudah ada, baik yang lokal maupun dunia. Saya telanjur mencap Puteri Salju sebagai perempuan nggak bener. Ya, masak sih dicium sekali sama pangeran trus mau menikah dan hidup bahagia dengannya? Pangeran di kisah itu juga aneh, masa sih mau-maunya cium bibir orang mati? Bukannya itu semacam kelainan seksual? Belum lagi Cinderella yang mau-maunya menikahi pangeran yang baru dikenalnya semalam demi kenaikan status. Ariel di puteri duyung ya delusif, menginginkan lebih dari yang seharusnya. Puteri Belle? Ah, dia pasti mengidap Stockholm Syndrom, jatuh cinta pada orang yang menyakitinya.
Di luar itu, bagian akhir dongeng yang mengatakan “mereka hidup bahagia selamanya” … ayolah! Enggak ada hal semacam itu di dunia. Kalimat seperti itu hanya akan membuat anak-anak perempuan berkhayal untuk “ditemukan” oleh pangeran kuda putih ketimbang mencari sendiri jati dirinya.
Dan dongeng Sangkuriang? Oh, saya telanjur mencapnya sebagai kisah paling aneh. Ada unsur bestialitas dan incest di sana. Dayang Sumbi “menikah” dengan seekor anjing lalu punya anak Sangkuriang yang ingin menikahi ibunya trus baper dan mengamuk karena ditolak. (Kadang mikir, mengingat begitu banyaknya gunung dan candi di Indonesia, jangan-jangan karena nenek moyang kita gampang baper. Ditolak dikit, nendang perahu. Ditolak dikit, bikin candi)
Dan begitulah seterusnya saya memandang kisah-kisah dongeng sebagai ‘nggak masuk akal’ dan ‘nggak mendidik’
Lantas implikasinya dengan kisah dongeng yang harus saya buat? Nggak ada secara langsung sih. Saya tetap bisa menyelesaikan naskah-naskah saya dengan baik. Tapi selama proses penulisan itu, saya “berantem” terus dengan ego saya, dengan pemikiran ‘orang dewasa’ saya, dengan idealisme saya. Bahkan saya sempat frustasi, merasa kerja saya sia-sia saja karena saya nggak suka materinya.
Sampai kemudian anak perempuan saya membaca hasil tulisan saya (waktu itu baru sekitar 65% selesai). Saya lumayan kaget karena dia berhasil menangkap pesan-pesan moral dalam kisah-kisah itu, enggak terdistorsi dengan logika. Selama ini saya enggak “provide” dia dengan dongeng-dongeng tersebut, dan lebih suka berkreasi dengan dongeng sendiri untuk menyampaikan pesan. Jadi, ini pertama kali juga dia tahu mengenai Cindelaras, Lebai Nan Malang, Sigarlaki dan Limbat, Joko Kendil dan lain sebagainya.
Dari komentar-komentarnya, saya belajar satu hal penting. DONGENG ADALAH DONGENG. Pikiran anak-anak beda banget dengan orang dewasa dalam melihat dongeng. Anak-anak lebih bisa menikmati sebuah kisah, sementara orang dewasa mencari logika dalam setiap kisah. Anak-anak tidak merasa perlu mencari klimaks dalam sebuah dongeng, sementara tanpa drama, orang dewasa akan melihat dongeng sangat membosankan.
Saya ingat waktu kecil baca kisah-kisah yang ada di majalah Bobo, dan terkesan banget dengan ceritanya. Dan sejatinya, dongeng-dongeng semacam itulah yang mendorong saya menulis dan menjadi penulis saat ini. Saya tergerak untuk membuat imajinasi saya nyata dalam bentuk tulisan, bukan sekedar khayalan di kepala.
Banyak pakar menyarankan orangtua untuk mendongeng. Banyak artikel parenting yang menekankan pentingnya sebuah dongeng bagi tumbuh kembang anak. Mendongeng, bukan saja memperkuat bonding, tapi juga semacam cara menghipnotis anak akan nilai-nilai moral kebaikan dan juga akhlak. Dan percaya deh, asalkan orangtua enggak mengganggu anak dengan logika orang dewasa, anak-anak dapat menangkap pesan-pesan tersebut dengan sangat baik.
Sekarang, saya sedang mengerjakan jilid kedua dari buku dongeng tersebut. Masih permintaan penerbit yang sama. Kali ini saya mengajak anak perempuan saya (yang juga suka nulis) untuk ambil bagian, dia menulis sekitar lima dongeng. Selain untuk nambah semangat, saya juga pingin tahu pendapat-pendapatnya yang jujur. Saya mencoba tidak lagi egois dan melihat dongeng dari kacamata sendiri.
Memang ada beberapa dongeng yang memberi kesan lemah, tapi tidak berarti kita lantas tidak akan membacakannya untuk anak. Anak-anak belajar untuk berpikir kritis melalui cerita dalam dongeng. Nggak percaya? Ingat diri sendiri saja waktu mendengar dongeng-dongeng tersebut? Apa ya kita jadi nggak baik hanya karena kalimat Cinderella dan pangeran hidup bahagia selamanya?





Tapi ngomong2 cewek skrg itu baik2 lho ya, cuma minta dingertiin. Cewek jaman dulu, minta dibikinin candi!